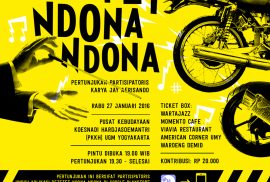“Yang Terhormat Ibu”
Pameran Retrospektif Sri Astari Rasjid
Seni Rupa, Tari, Wayang
27 Februari-4 Maret 2016
Di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri/PKKH
Jl. Pancasila UGM, Bulaksumur, Yogyakarta.
SRI ASTARI RASJID akan menggelar pameran retrospektif yang menampilkan karya-karya lukisan, fotografi, patung dan seni instalasi. Seniman yang lahir 26 Maret 1953 ini telah menampilkan karya-karyanya dalam berbagai pameran penting di banyak negara, di antaranya di Jakarta, Hongkong, Washington, New York, Moskow, Madrid, London, Paris, Beijing, Venezia Biennale, dan lain-lain. Ia juga telah memenangi beberapa kompetisi senirupa, di antaranya Nokia Arts Award, Phillip Morris Arts Award dan Winsor & Newton Award. Pada tahun 2016 ini, Astari telah dilantik sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia, berkedudukan di Sofia. Astari adalah Duta Besar perempuan pertama yang berlatar belakang seniman profesional.
Pameran yang dikuratori oleh Wicaksono Adi ini akan dibuka oleh GKR Hemas pada:
Sabtu, 27 Februari 2016
Pukul 19.00 WIB
Pada acara pembukaan akan ditampilkan tari Bedhaya Kontemporer berjudul “Garba”, koreografi oleh Retno Sulistyorini.
Pada:
Minggu, 28 Februari 2016
Pukul 19.00-04.00 WIB akan digelar Pementasan Tembang-Puisi Jawa oleh kelompok Wijijawa, dilanjutkan pergelaran Wayang Kulit semalam suntuk oleh Dalang Ki Seno Nugroho dengan lakon “Banjaran Kunti”.
Selama karirnya sebagai seniman Astari banyak mengembangkan bentuk-bentuk simbolik yang berkaitan dengan unsur dasar yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu daya maskulin dan feminin. Yaitu dua potensi daya atau energi yang dimiliki setiap individu dan dapat tumbuh atau berkembang sesuai dengan konteks sosio-historis yang berbeda-beda. Dua daya tersebut tak semata-mata merujuk pada jenis kelamin (gender) karena setiap jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) mengandung potensi yang sama, dan jika muncul kecenderungan dominan dari salah satu daya maka hal itu selalu berkaitan dengan karakteristik budaya tempat si manusia hidup.
Secara khusus, Astari banyak mengambil inspirasi karya-karyanya dari kultur asalnya, yaitu kultur Jawa. Astari menegaskan: “saya memandang Jawa sebagai rahim kultural di mana saya lahir dan kemudian menjelajah ke mana saja dan sebagai tempat saya pulang. Dalam upaya menggali dan memahami daya feminin dan maskulin, saya bertolak dari kekayaan khazanah budaya Jawa. Saya tertarik pada garis tegangan antara daya feminin dan maskulin, di mana hubungan antara dua daya tersebut tidak selalu mutlak dan permanen, melainkan dapat terus bergeser dan selalu terdapat negosiasi di antara keduanya. Garis tegangan dua posisi itu juga saya lihat dalam konteks kebudayaan modern dan global.”
Pameran ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya.